-

-
-
Loading

Loading

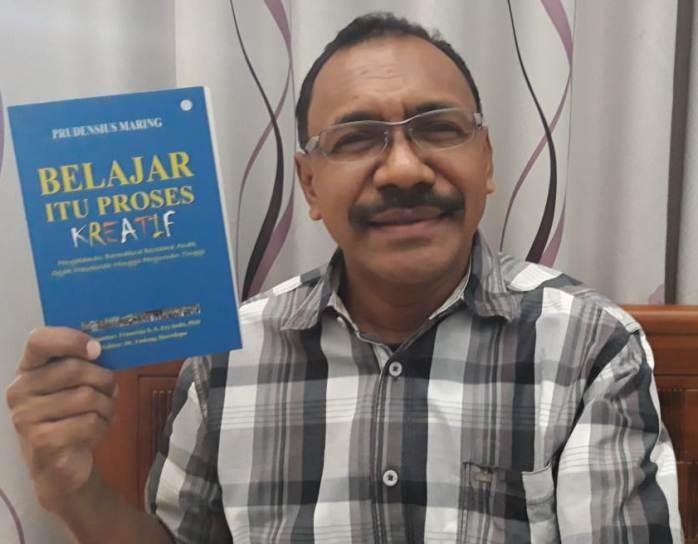 DR Prudensius Maring. (Istimewa)
DR Prudensius Maring. (Istimewa)
Oleh: DR Prudensius Maring
TEKNOLOGI INFORMASI yang kian canggih, nyaris membongkar habis dan menyodorkan semua kejadian atau peristiwa melalui aneka pemberitaan. Pun kejadian-kejadian di NTT dalam hitungan dua bulan terakhir. Gubernur (Gubernur dan Wakil Gubernur) telah melakukan gebrakan melalui kata dan perbuatan yang mencengangkan.
Tidak hanya mengagetkan zona birokrasi dan legislatif, kini merambah ke zona Gereja dan masyarakat luas. Bagai bulan madu dengan suguhan kopi pahit diseduh brotowali. Yang tak biasa merasakan pahit getir hingga mengernyitkan dahi. Yang terbiasa pasti berujar, nah ini baru cocok!
Baca juga:
Virus PHKHentakan MengagetkanOrang NTT suka berdendang dan menari. Hentakan kaki dengan aba-aba: satu, dua, tiga, putar ke kiri dan putar ke kanan adalah biasa. Itu selalu disambut riang gembira. Tat kala musik berakhir selalu akan disambut tarikan nafas sesal dan omelan. Negosiasi perpanjangan waktu dengan tuan pesta kerap dilakukan.
Tapi hentakan-hentakan yang mengemuka belakangan ini terasa beda. Gubernur dan Wakil Gubernur yang memang pandai menari itu sedang menyajikan hentakan beda nuansa dan isi. Pelantikan mereka tanpa pesta. Itu menghentikan kebiasaan hentakan kaki di sebuah pesta raya pelantikan.
Baca juga:
Nurani Antropologi KekuasaanTak lama berselang, riuh rendah menyambut moratorium tambang dan pengiriman TKI. Tulang kaki perusahaan TKI nakal siap dipatahkan. Yang ternina boboh dalam praktek buruk kebiasaan lama, berteriak-teriak menggugat. Bahasa simbolik yang mudah dibaca itu, sengaja ditarik makna lurus-lurus seraya melempar umpan ke publik agar hati-hati karena pemimpin kita seolah “mau main kasar”.
Kecemasan itu tak berakhir. Pesan simbolik menyasar pengusaha nakal itu itu berbalik kena tulang sendiri. Dalam suatu peristiwa, bukanya kaki pengusaha nakal yang dicederai, eh malah tulang kaki sendiri - sang eksekutif yang dinilai lalai. Itu terwadah dalam sebuah peristiwa mutasi pejabat tata kelola per-TKI-an. Itu lantas menuai tudingan sebagai pelanggaran aturan formal.
Tak cuma dalam bilik otoritas eksekutif. Hal menghebohkan justru berlangsung di bilik legislatif. Kaum yang biasa terjaga wibawa, tiba-tiba terhenyak bukan oleh hentakan biasa – tapi malah menyerupai bentakan: “Kau diam”. Dewan yang biasa pegang teguh pada tata tertib sebagai benteng penundukan kaum yang lain (seringnya eksekutif), seolah rontok wibawa. Ketegangan yang sempat menyeruak, lalu terdiam, entah apa yang terjadi. Di pinggiran jalan sayup-sayup terdengar suara rakyat: Ini baru cocok!
Hari-hari belakangan ini, hentakan menyambar zona yang jarang tersentuh. Gubernur NTT menyodorkan pikiran baru. Lebih kurang begini: “Orang kaya masuk surga, orang miskin tak masuk surga”. Geliat reaksi beraneka rupa. Ada yang menyebut, kali ini blunder. Itu lalu dikaitkanlah dengan model/teori etika protestan, dan lainnya. Tapi ada juga obrolan di warung kopi yang menyatakan bahwa pernyataan Gubernur itu relevan.
Membaca Hentakan PerubahanPeristiwa di atas bisa disusun tambah panjang. Itu satu hal. Hentakan itu dilakukan oleh Gubernur, pemimpin harapan rakyat NTT. Itu hal kedua. Ini terjadi segera setelah dilantik dan mengagetkan banyak orang. Itu hal ketiga. Berikutnya, meski pro-kontra tapi Gubernur terus jalankan aksinya dengan enteng dan lugas. Itu semua mengundang tanya: Ada apa di balik itu semua?
Saya membaca, hentakan awal Gubernur ini “ada maunya”. Kemauan terkuatnya adalah melakukan perubahan besar agar masyarakat NTT sejahtera dengan lingkungan sosial dan fisik yang damai-tentram dan lestari-berkelanjutan. Bacaan demikian bisa diabstrakasi dari berbagai buah pikir, komitmen, dan tindakan riil yang dilakukan dwitunggal pemimpin NTT saat ini pada berbagai ruang dan waktu.
Sejumlah pesan kunci bisa ditarik dari serangkaian hentakan di atas. Pertama, pesan soal pentingnya sikap tegas kepemimpinan. Kedua, soal keberpihakan sungguh-sunguh pada derita rakyat dengan melakukan eksekusi kebijakan dan tindakan. Ketiga, soal kerja keras yang tidak asal kerja. Keempat, soal pentingnya kekuasaan (legislatif dan eksekutif) demi rakyat bukan demi wibawa diri. Kelima, soal yang amat penting adalah menegaskan bahwa akselerasi perubahan harus dimulai dari pendasaran mindset (pola dan cara berpikir) yang benar.
Seruan moratorium, kasih “patah kaki” (sebagai sebuah pesan simbolik), dan pencopotan pejabat perlu dibaca sebagai signal ketegasan pemimpin. Yang mestinya tidak sekadar ditonton para pemimpin lainnya di NTT, tapi ditransformasi dan dijalankan ke level dan bidang-bidang lain - tempat dan waktu di mana sosok pemimpin dinanti rakyat. Sepertinya, pemimpin baru kita gerah dengan pemimpin yang gemar beretorika tanpa eksekusi perubahan.
Pencopotan pejabat, pengetatan jam kerja ASN, sanksi pengenaan rompi bagi yang tidak disiplin, perlu dibaca sebagai upaya menjaga harkat dan martabat pelayanan. Harkat dan martabat pelayanan terletak pada totalitas pelayanan. Sebaliknya, mentalitas terlambat, membolos, titip absen, dan membubuhkan tanda tangan tanpa konfirmasi adalah pelemahan atas harkat dan martabat pelayanan. Totalitas pelayanan harus melekat dan bekerja dalam diri aparatur Negara.
Hentakan di gedung dewan yang berpotensi memicu kontraksi relasi politik legislatif-eksekutif dan pemecatan pejabat mesti dibaca dalam spirit keinginan mengubah paradigma relasi kekuasaan yang dinamis. Orientasi pada pelayanan kepentingan rakyat ketimbang menjaga kewibawaan kekuasaan. Legislatif dan eksekutif mestinya melebur menjadi kekuatan kepemimpinan yang efektif buat rakyat. Bukan berkutat dengan tata cara dan memelihara kelaziman belaka. Hentakan ini bila direspon secara proaktif, justru akan memberi warna baru dalam masa bulan madu pejabat baru dengan jajaran birokrasi dan legislatif.
Hentakan terkini soal “siapa yang layak masuk surga” jelas-jelas sebuah oto-kritik sekaligus upaya mengonstruksi mindset perubahan. Tercetusnya pernyataan “orang miskin” tidak masuk surga bisa jadi karena terbaca oleh Gubernur bahwa kita orang kerap berlindung di balik pernyataan “orang kaya sulit masuk surga” maka tidak apa-apa kita jadi orang miskin saja. Perubahan dimulai dari konstruksi pikiran. Pikiran bahwa orang miskin dan malas tidak masuk surga diharapkan menggerakkan kita menjadi rajin agar jadi kaya dalam arti luas – supaya masuk surga.
Analogi yang mirip banyak kita jumpai dalam wajah lain. Misalnya, jika petani berpikir aktivitas bertaninya sebagai sebuah rentang siklus maka ia menanam “secukupnya saja” tahun ini karena musim berikut bisa tanam lagi. Musim tanam birkan saja berlalu toh nanti akan ada musim tanam berikut. Karena tahun ini panen raya maka tahun depan berhenti bekerja, tunggu stok di lumbung habis baru kerja kebun lagi. Manusia hidup harus ada hutang, maka kita tidak malu-malu pinjam uang sana sini meski hanya sekadar buat pesta pora. Hal-hal ini, mesti jadi agenda hentakan berikutnya.
Sesungguhnya, kehidupan orang NTT terbalut-ikat erat dengan basis spiritualitas. Sumber berlimpah dari nilai keagamaan modern dan religiositas tradisional (keyakinan dan kepercayaan) tak bisa disangkal. Tapi mengapa kita sulit mentransformasi itu menjadi basis mentalitas dan sikap-perilaku tangguh. Kerap ada kontradiksi, kita bisa menjadi orang taat beragama dan penjaga nilai adat yang handal namun tak sebanding wujudnya dalam tindakan dan perilaku kita.
Hal-hal di atas nampaknya hendak diperbarui kepemimpinan NTT saat ini. Mungkin Gubernur hendak membongkar dan memurnikan mindset atau pola/cara berpikir lama untuk diganti dengan pola/cara berpikir baru agar kita bisa berlari cepat bersama gerbong perubahan.
Soliditas Arah PerubahanSaya meyakini prinsip bahwa “satu hentakan peristiwa bisa dimaknai beragam”. Tergantung sudut pandang dan kepentingan. Pada titik inilah perlu ada proses memoderasi agar membuat terang benderang makna yang tersirat di balik hentakan-hentakan yang dilakukan Gubernur. Perlu dibangun komunikasi dan penjelasan secara lugas, sabar, dan persuasif yang dilakukan secara luas dan mendalam. Tidak saja kepada pimpinan di lingkup eksekutif dan legislatif, tetapi juga kepada publik.
Kita bisa menginspirasi kepada perspektif dinamika sosial. Model ini memberi pesan yang kuat bahwa perubahan sosial butuh dukungan soliditas ikatan ide/gagasan, soliditas ikatan normatif, dan soliditas ikatan tindakan bersama. Pertama, soal soliditas ide/gagasan. Ide-ide untuk perubahan bisa datang dari satu dua orang aktor. Namun para pencetus ide punya tanggung jawab untuk membenihkan dan menyebarluaskan ide perubahan agar tercipta ide dan kesadaran kolektif untuk berubah.
Itu artinya, penguasaan ide/gagasan perubahan tidak cukup hanya ada pada Gubernur. Ide/gagasan perubahan yang dimiliki (yang mungkin terwadah dalam visi) mesti ditansformasi secara luas dan lugas, entah kepada eksekutif maupun legislatif dan lainnya. Proses itu harus dilakukan secara terbuka, mendalam, dan matang. Itu agar para kadis, kepala biro, dan aparatur pelaksana, serta para Bupati dan jajarannya di tingkat kabupaten tidak asal bergerak melompat ke sana kemari sekadar menyamakan langkah, tapi gerakan atas dasar kesamaan ide/gagasan perubahan.
Kedua, soal ikatan normatif bersama. Para pencetus ide/gagasan perubahan harus mampu melahirkan ikatan normatif sebagai panduan gerak bersama. Moratorium TKI dan tambang, misalnya, perlu ditingkatkan menjadi ikatan normatif bersama, entah dalam bentuk Perda, Pergub, atau instrumen kebijakan atau aturan lain yang mengikat secara normatif-kolektif. Ini penting agar ide perubahan yang tercetus tidak melahirkan interpretasi berbeda di tangan aktor lain, pada garis ke samping atau garis ke bawah.
Ketiga, soal ikatan tindakan bersama. Banyak pemimpin baru kerap sukses membangun ide/gagasan perubahan hingga melahirkan ikatan normatif, namun kerap gagal menurunkan dalam tindakan. Visi baru tanpa pendekatan baru, misi baru tanpa metode kerja baru, program/proyek baru tanpa insrumen penilaian baru. Itu kerap membuat nasib perubahan tidak berlanjut, hanya seumur jabatan pemimpin atau bahkan hanya seumur proyek. Kerap para pemimpin mengantongi visi baru, namun aparatur Negara pada level pelaksana tetap mendekap pendekatan lama, mengulang metode usang, dan mensakralkan instrumen penilaian capaian sekadar pemenuhan administratif.
Dalam perspektif perubahan berkelanjutan, hentakan Gubernur saat ini masih ada pada fase diferensiasi awal, yang melahirkan pro-kontra dan konstrasi sosial. Geliat ini perlu didorong menuju tiga fase berikut yaitu terjadi perbaikan adaptif di mana birokrat dan masyarakat beradaptasi dan siap diri mewujudkan tujuan baru. Lalu menuju fase integrasi yang ditandai sikap-perilaku mengadopsi cara pandang baru dan metode/cara kerja baru dan mulai ada hasil baru. Jika itu mulai bersemi, pemimpin perlu mendorong terjadinya generalisasi nilai dan perilaku kolektif agar gerbong perubahan yang diinisiasi ini berkelanjutan.
Para pemimpin formal transformatif mesti menyadari bahwa waktu efektifnya adalah 5 tahun meski ada potensi tambahan waktu 5 tahun. Karenanya ia harus memanfaatkan waktu terbatas itu untuk membenihkan ide bersama, membangun kerangka normatif bersama, dan mengikat tindakan kolektif. Garap semua itu melalui fase diferensiasi, perbaikan adaptif yang sabar, proses integrasi, dan generalisasi nilai kolektif demi perubahan berkelanjutan. Salam perubahan!
Penulis adalah Direktur Institut Antropologi Kekuasaan. Penulis buku “Belajar Itu Proses Kreatif”Dosen/Peneliti, Jakarta.